Kenapa kadang sebuah negara sudah menambah jumlah uang beredar, tapi pertumbuhan ekonominya tetap melambat? Kenapa juga saat krisis, uang yang seharusnya mendorong konsumsi justru malah disimpan di tabungan? Jawaban dari teka-teki ini bisa kamu temukan dalam konsep yang disebut Velocity of Money, atau kecepatan perputaran uang.
Velocity of Money sering disebut sebagai indikator penting kesehatan ekonomi. Namun, apakah benar ia masih relevan di era modern, termasuk di Indonesia dan bahkan dalam ekosistem kripto? Artikel ini akan membawamu menyusuri sejarah, rumus, hingga kelemahannya, lengkap dengan data terbaru agar kamu bisa melihat apakah konsep ini benar-benar “kunci ekonomi” atau sekadar mitos yang sudah usang.
Apa Itu Velocity of Money?
Sebelum membahas lebih dalam, kamu tentu perlu tahu dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan velocity of money. Secara sederhana, velocity of money adalah ukuran seberapa cepat uang berpindah tangan dalam suatu perekonomian. Dengan kata lain, ia mengukur berapa kali satu unit mata uang digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam periode tertentu.
Rumus paling umum untuk menghitungnya adalah:

GDP nominal di sini merepresentasikan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan, sementara money supply bisa dilihat dari M1 (uang tunai dan simpanan transaksi) atau M2 (M1 ditambah tabungan dan deposito). Konsep ini erat kaitannya dengan inflasi, karena kecepatan peredaran uang bisa ikut menentukan tekanan harga di pasar.
Konsep ini juga lahir dari persamaan klasik ekonomi yang disebut Equation of Exchange:
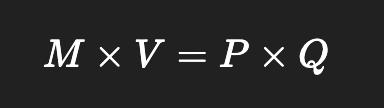
di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah velocity, P adalah tingkat harga, dan Q adalah jumlah output riil.
Setelah tahu definisinya, wajar kalau muncul pertanyaan: siapa yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang velocity of money ini?
Sejarah & Tokoh Pemikir di Balik Konsep Ini
Konsep velocity of money ternyata bukan barang baru. Jauh sebelum istilah ini diformalkan, ekonom klasik seperti David Hume dan John Stuart Mill sudah menyinggung pentingnya kecepatan uang berpindah tangan. Mereka menyadari bahwa uang tidak hanya soal jumlah, tapi juga soal bagaimana uang itu digunakan oleh masyarakat.
Barulah di tahun 1911, ekonom Amerika Irving Fisher memformalkan konsep ini dalam bukunya The Purchasing Power of Money. Dialah yang memperkenalkan persamaan MV = PQ dan menjadikan velocity sebagai indikator resmi dalam analisis moneter.
Seiring berjalannya waktu, banyak ekonom lain yang ikut memberi warna. John Maynard Keynes pada 1930-an menyebut velocity sebagai variabel yang tidak stabil karena sangat dipengaruhi psikologi masyarakat. Sementara itu, Milton Friedman dan kaum monetaris pada era 1970-an justru beranggapan velocity relatif stabil dalam jangka panjang, sehingga bisa dijadikan dasar kebijakan berbasis jumlah uang beredar.
Dari sejarah ini, kita bisa melihat bahwa velocity bukanlah konsep yang berdiri di ruang hampa. Ia lahir dari perdebatan panjang para ekonom. Lalu, bagaimana peran dan fungsinya dalam ekonomi modern?
Fungsi & Pentingnya Velocity of Money
Kalau dilihat dari sisi teori, velocity of money punya beberapa fungsi penting. Pertama, ia bisa menjadi indikator kesehatan ekonomi. Kalau velocity tinggi, artinya uang cepat berpindah tangan, konsumsi tinggi, dan aktivitas ekonomi berjalan aktif. Sebaliknya, velocity rendah biasanya menunjukkan masyarakat lebih memilih menyimpan uang, yang bisa mengindikasikan ekonomi sedang lesu.
Kedua, velocity juga berkaitan erat dengan inflasi. Semakin cepat uang beredar, semakin tinggi pula risiko inflasi. Sebaliknya, jika velocity menurun, risiko deflasi bisa meningkat. Inilah sebabnya bank sentral memperhatikan velocity ketika menilai efektivitas kebijakan moneter.
Namun, velocity tidak bisa berdiri sendiri. Ada banyak indikator lain yang mempengaruhinya. Maka dari itu, mari kita bahas faktor-faktor yang biasanya menentukan cepat atau lambatnya velocity of money.
Indikator yang Mempengaruhi Velocity
Kamu perlu tahu bahwa velocity of money dipengaruhi oleh banyak hal, bukan hanya sekadar jumlah uang yang dicetak. Beberapa indikator utama antara lain:
- Inflasi: Ketika harga naik cepat, orang cenderung segera membelanjakan uang sebelum nilainya turun. Ini bisa mendorong velocity meningkat.
- Suku bunga acuan: Ketika bank sentral menaikkan suku bunga, masyarakat cenderung lebih suka menabung daripada membelanjakan uang. Akibatnya velocity turun. Namun dalam jangka panjang, suku bunga yang stabil justru bisa menopang pertumbuhan ekonomi.
- Pertumbuhan ekonomi (GDP): Semakin tinggi pertumbuhan, semakin aktif pula uang berpindah tangan.
- Pembayaran digital (e-money): Logikanya bisa mempercepat transaksi, tapi data di Indonesia justru menunjukkan hubungan negatif dalam jangka panjang karena uang lebih banyak tersimpan di sistem digital.
- Nilai tukar & IHSG: Fluktuasi nilai tukar rupiah atau kinerja pasar saham bisa mempengaruhi kepercayaan konsumen, yang pada akhirnya berdampak ke velocity.
- Krisis & pandemi: Situasi luar biasa seperti COVID-19 membuat masyarakat menahan pengeluaran, sehingga velocity anjlok.
Kalau indikator-indikator ini kita perhatikan, barulah jelas kenapa velocity bisa sangat berbeda antara satu negara dengan negara lain. Mari kita bandingkan data di tingkat global dan Indonesia.
Data Terbaru Velocity of Money: Global vs Indonesia
Di Amerika Serikat, data dari Federal Reserve (FRED) menunjukkan tren velocity M2 yang menarik. Velocity sempat naik tinggi dari era 1960-an sampai 2000-an, lalu anjlok tajam sejak krisis keuangan global 2008. Saat pandemi COVID-19, velocity jatuh ke titik terendah, meskipun suplai uang melonjak akibat stimulus besar-besaran.
Bagaimana dengan Indonesia? Data Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan M2 rata-rata 6–7% per tahun, sementara GDP nominal naik sekitar 5% per tahun. Akibatnya, velocity relatif stagnan bahkan cenderung menurun. Artinya, meskipun uang beredar makin banyak, masyarakat cenderung menahan uangnya di tabungan dan deposito. Fenomena ini mirip dengan pola pengelolaan keuangan pribadi, di mana orang lebih fokus menabung daripada membelanjakan atau berinvestasi.
Perbandingan ini memberi gambaran bahwa velocity tidak selalu bergerak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Setelah melihat data, wajar kalau muncul pertanyaan: apakah konsep velocity ini juga berlaku di sektor lain seperti saham, forex, dan kripto?
Velocity dalam Saham, Forex, dan Kripto
Menariknya, konsep velocity tidak hanya ada di ekonomi makro. Dalam dunia saham, ada metrik mirip velocity yaitu turnover ratio, yang mengukur seberapa sering saham berpindah tangan di bursa. Saham gorengan biasanya punya turnover tinggi, sementara saham blue-chip lebih stabil.
Di forex, velocity bisa dilihat dari seberapa cepat mata uang berpindah di pasar internasional. Dolar AS, misalnya, punya velocity tinggi karena jadi standar dalam perdagangan global.
Di dunia kripto, konsep ini makin relevan. Token velocity digunakan untuk menilai apakah suatu koin punya utility nyata, dan ini berkaitan dengan strategi cara investasi kripto yang tepat sesuai profil risiko kamu. Stablecoin seperti USDT biasanya punya velocity tinggi karena sering dipakai transaksi, sementara Bitcoin lebih sering di-HODL, sehingga velocity-nya rendah.
Namun, dengan segala penerapannya, apakah velocity of money ini bisa dianggap sebagai pakem mutlak?
Kelemahan Konsep Velocity of Money
Walaupun terlihat sederhana dan elegan, velocity of money punya sisi rapuh yang sering diabaikan. Pertama, rumus MV = PQ hanya menawarkan kerangka linear. Ia seakan menyiratkan hubungan langsung antara jumlah uang dan output ekonomi, padahal perilaku manusia jauh lebih kompleks. Orang bisa memilih menabung, berinvestasi, atau bahkan menimbun aset dalam bentuk lain, sehingga hubungan itu tidak sesederhana hitungan matematika.
Kedua, kestabilan velocity ternyata mitos. Keynes sudah mengingatkan sejak 1930-an bahwa velocity bisa berubah karena faktor psikologis, dan data modern membuktikannya. Di Amerika Serikat, velocity sempat turun tajam setelah krisis 2008, meski ekonomi perlahan pulih. Pandemi COVID-19 kembali menegaskan bahwa meskipun suplai uang melonjak akibat stimulus, masyarakat lebih memilih menyimpannya alih-alih membelanjakannya.
Ketiga, masalah pengukuran. Apakah harus pakai M1, M2, atau bahkan M3? Hasilnya bisa berbeda jauh. Di era digital, muncul lagi tantangan baru: shadow banking, fintech, hingga stablecoin yang tidak tercatat resmi. Semua ini membuat definisi money supply kabur dan membuat velocity semakin sulit dijadikan pegangan pasti.
Kalau kita lihat ke Indonesia, Bank Indonesia juga tidak menjadikan velocity sebagai indikator utama. Fokus mereka tetap pada inflasi, suku bunga, dan konsumsi rumah tangga. Itu artinya, di level kebijakan pun velocity dianggap punya keterbatasan praktis.
Dengan semua kelemahan itu, wajar kalau muncul pertanyaan: apakah velocity of money masih relevan di era modern yang penuh dengan inovasi finansial?
Apakah Masih Relevan di Era Modern?
Jawabannya, masih ada relevansinya, tapi posisinya sudah bergeser. Di tingkat global, bank sentral seperti Federal Reserve atau ECB tidak lagi menjadikan velocity sebagai kompas utama kebijakan moneter. Mereka lebih fokus pada target inflasi, suku bunga acuan, dan ekspektasi pasar. Velocity lebih sering diperlakukan sebagai indikator pelengkap untuk memahami perilaku masyarakat terhadap uang.
Namun, di konteks akademik dan analisis, velocity tetap bernilai. Misalnya, ia bisa mengungkap fenomena menarik: kenapa stimulus moneter tidak selalu langsung mendorong inflasi, atau kenapa ekonomi tetap bisa tumbuh meski velocity stagnan. Dalam konteks Indonesia, velocity bisa membantu membaca kecenderungan masyarakat—apakah mereka lebih suka menabung, berinvestasi, atau membelanjakan uang untuk konsumsi.
Menariknya, justru di dunia kripto, konsep velocity kembali menemukan panggung. Token velocity menjadi salah satu alat penting dalam tokenomics. Kalau sebuah koin diperdagangkan dan digunakan aktif (misalnya stablecoin untuk pembayaran), velocity-nya tinggi. Kalau justru disimpan untuk spekulasi seperti Bitcoin, velocity-nya rendah. Dari sini kita bisa menilai apakah sebuah aset lebih cocok disebut “alat transaksi” atau “store of value”.
Jadi, meskipun tidak lagi jadi bintang utama di kebijakan moneter, velocity tetap punya peran: sebagai cermin tambahan untuk memahami dinamika ekonomi modern, dari negara maju hingga ekosistem kripto.
Kesimpulan
Velocity of Money memang lahir dari teori klasik Irving Fisher lebih dari seabad lalu, tapi perdebatan tentangnya masih relevan sampai hari ini. Data global dan Indonesia menunjukkan satu hal penting: uang yang banyak beredar tidak selalu menjamin ekonomi bergerak cepat. Kalau velocity rendah, uang bisa saja mengendap di tabungan atau deposito tanpa memberi dampak signifikan ke aktivitas ekonomi.
Artinya, kamu tidak bisa hanya melihat jumlah uang beredar untuk menilai kondisi ekonomi. Velocity harus dibaca bersama indikator lain seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan cara itu, gambaran ekonomi jadi lebih utuh.
Insight yang bisa kamu tarik adalah: velocity bukanlah “kitab suci” ekonomi, tapi ia adalah lensa tambahan. Ia bisa membantu menjelaskan kenapa krisis finansial bisa bertahan lama meski stimulus sudah digelontorkan, atau kenapa mata uang digital tertentu lebih hidup dalam ekosistemnya. Dalam dunia kripto, velocity bahkan bisa menentukan apakah sebuah token benar-benar punya utilitas atau hanya jadi alat spekulasi. Sama halnya ketika kamu mencoba membaca cara prediksi harga kripto, memahami velocity bisa jadi lensa tambahan agar analisis lebih tajam.
Jadi, pada akhirnya, Velocity of Money adalah kunci untuk memahami perilaku uang, tapi bukan jawaban tunggal atas semua masalah ekonomi. Ia penting untuk kamu pahami, tapi harus selalu dilihat berdampingan dengan indikator lain agar analisismu tidak menyesatkan.
Itulah informasi menarik tentang Velocity of Money yang bisa kamu eksplorasi lebih dalam di artikel populer Akademi crypto di INDODAX. Selain memperluas wawasan investasi, kamu juga bisa terus update dengan berita crypto terkini dan pantau langsung pergerakan harga aset digital di INDODAX Market.
Untuk pengalaman trading yang lebih personal, jelajahi juga layanan OTC trading kami di INDODAX. Jangan lupa aktifkan notifikasi agar kamu selalu mendapatkan informasi terkini seputar aset digital, teknologi blockchain, dan berbagai peluang trading lainnya hanya di INDODAX Academy.
Kamu juga dapat mengikuti berita terbaru kami melalui Google News untuk akses informasi yang lebih cepat dan terpercaya. Untuk pengalaman trading yang mudah dan aman, download aplikasi crypto terbaik dari INDODAX di App Store atau Google Play Store.
Maksimalkan juga aset kripto kamu dengan fitur INDODAX Earn, cara praktis untuk mendapatkan penghasilan pasif dari aset yang kamu simpan. Segera register di INDODAX dan lakukan KYC dengan mudah untuk mulai trading crypto lebih aman, nyaman, dan terpercaya!
Kontak Resmi Indodax
Nomor Layanan Pelanggan: (021) 5065 8888 | Email Bantuan: [email protected]
Ikuti juga sosial media kami di sini: Instagram, X, Youtube & Telegram
FAQ
1. Apa itu velocity of money?
Velocity of money adalah rasio PDB nominal dengan jumlah uang beredar, yang menunjukkan seberapa cepat uang berpindah tangan dalam ekonomi.
2. Bagaimana cara menghitung velocity of money?
Caranya sederhana: bagi GDP nominal dengan jumlah uang beredar (M1 atau M2).
3. Apa faktor yang mempengaruhi velocity of money?
Inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, e-money, nilai tukar, hingga kepercayaan masyarakat.
4. Mengapa velocity of money bisa turun?
Biasanya karena krisis, pandemi, atau ketika masyarakat lebih memilih menahan uang di tabungan daripada belanja.
5. Apakah konsep ini berlaku di saham, forex, dan kripto?
Ya. Di saham ada turnover ratio, di forex ada circulation rate, dan di kripto ada token velocity.
6. Apa kelemahan velocity of money?
Konsepnya terlalu sederhana, tidak stabil, sulit diukur, dan tidak lagi jadi acuan utama dalam kebijakan moneter modern.






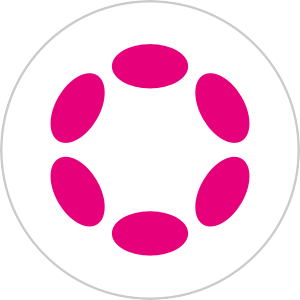 Polkadot 8.91%
Polkadot 8.91%
 BNB 0.45%
BNB 0.45%
 Solana 4.80%
Solana 4.80%
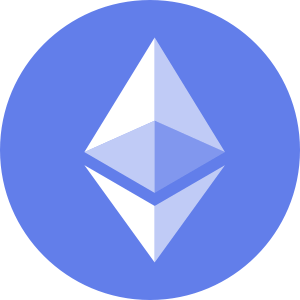 Ethereum 2.37%
Ethereum 2.37%
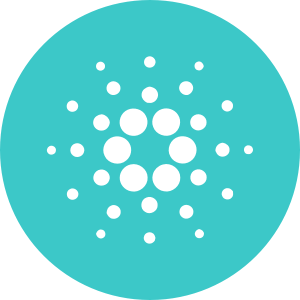 Cardano 1.65%
Cardano 1.65%
 Polygon Ecosystem Token 2.13%
Polygon Ecosystem Token 2.13%
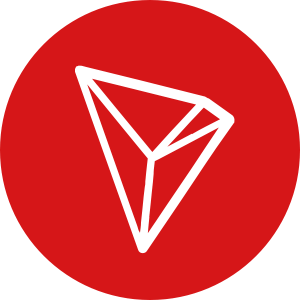 Tron 2.85%
Tron 2.85%
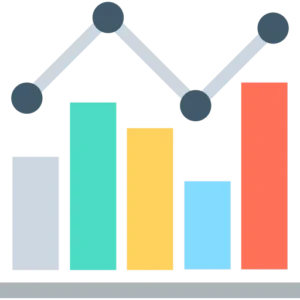 Pasar
Pasar


